Jakarta. November. Di tengah gemuruh globalisasi, seni dan budaya Indonesia tampak kembang-kempis seperti napas yang mulai tercekat oleh debu modernitas. Dulu ia tegak berdiri—gagah, anggun, mekar di setiap halaman kehidupan—namun kini perlahan tergeser oleh budaya luar yang masuk begitu cepat, begitu deras, dan seringkali tanpa filter makna.

Kita mulai bertanya dalam hati:
Akankah toleransi budaya yang dulu menghangatkan kini justru terasa berjarak?
Akankah kita terus membuka pintu, namun lupa menjaga rumah sendiri?
Di setiap perhelatan besar, khususnya Pesta Peringatan, Festival Kota, Hari Jadi Daerah, hingga peringatan nasional, perlombaan bernuansa etnis kini hadir dengan warna yang semakin tipis—seperti batik yang luntur setelah dicuci terlalu sering.
Dulu, setiap panggung peringatan dipenuhi aroma tanah Nusantara:
-
gamelan yang bergetar halus,
-
tari tradisi yang dilatih turun-temurun,
-
nyanyian rakyat yang membawa riwayat nenek moyang,
-
baju adat yang penuh filosofi,
-
teater tradisi yang menyimpan pesan moral zaman dahulu.
Namun kini, panggung itu lebih sering dihiasi oleh gaya luar yang cepat viral, lucu, dan serba instan.
Bukan salah modernitas—tetapi ketika nilai lokal mulai dirasakan sebagai “beban”, ketika seni tradisi dianggap tidak seksi untuk konten, di situlah kita tahu ada yang retak.

Perlombaan bernuansa etnis yang dulu sakral kini berubah jadi sekadar formalitas.
Sering kita lihat:
-
Tari daerah dipadatkan menjadi dua menit demi mengejar durasi.
-
Lagu tradisi diganti musik elektronik demi menarik penonton.
-
Makna filosofis pakaian adat dihilangkan, diganti dekorasi sekadarnya.
-
Generasi muda tampil, tetapi tanpa pemahaman—sekadar “ikut lomba”.
Apa yang tinggal?
Bentuk tanpa jiwa. Tradisi tanpa makna. Pementasan yang indah tapi kosong.
Sementara itu, budaya luar semakin disambut hangat tanpa seleksi nilai. Kita membanggakan toleransi, namun lupa bahwa toleransi tanpa akar bisa berubah menjadi penyerahan diri.
Yang menjadi pertanyaan:
Apakah toleransi kita akan terus meluas hingga kita tak lagi dapat merasakan jaraknya—jarak yang seharusnya menjaga identitas?
**Seni dan budaya Indonesia tidak boleh hanya menjadi ornamen.
Ia harus tetap menjadi napas, menjadi denyut, menjadi alasan kita berdiri sebagai bangsa.**

Kembang-kempis seni tradisi ini bukan tanda melemah, tetapi tanda bahwa kita harus menolongnya bernapas lagi.
Perhelatan-perhelatan besar harus kembali menjadi panggung yang memperkuat akar:
-
lomba etnis harus memuliakan nilai, bukan sekadar memajang kostum,
-
musik tradisi harus dihidupkan, bukan dicampurkan tanpa arah,
-
generasi muda harus diajak merasakan makna, bukan hanya tampil,
-
seni harus menjadi ruang pendidikan, bukan sekadar hiburan sesaat.
Karena budaya bukan hanya masa lalu.
Ia fondasi dari masa depan yang bercahaya.
Dan dari napas yang kembang-kempis ini, kita masih bisa menanamkan keyakinan:
Selama ada yang peduli, selama masih ada yang bersuara,
seni dan budaya kita akan kembali bernapas penuh—dan berdiri tegak melampaui zaman.








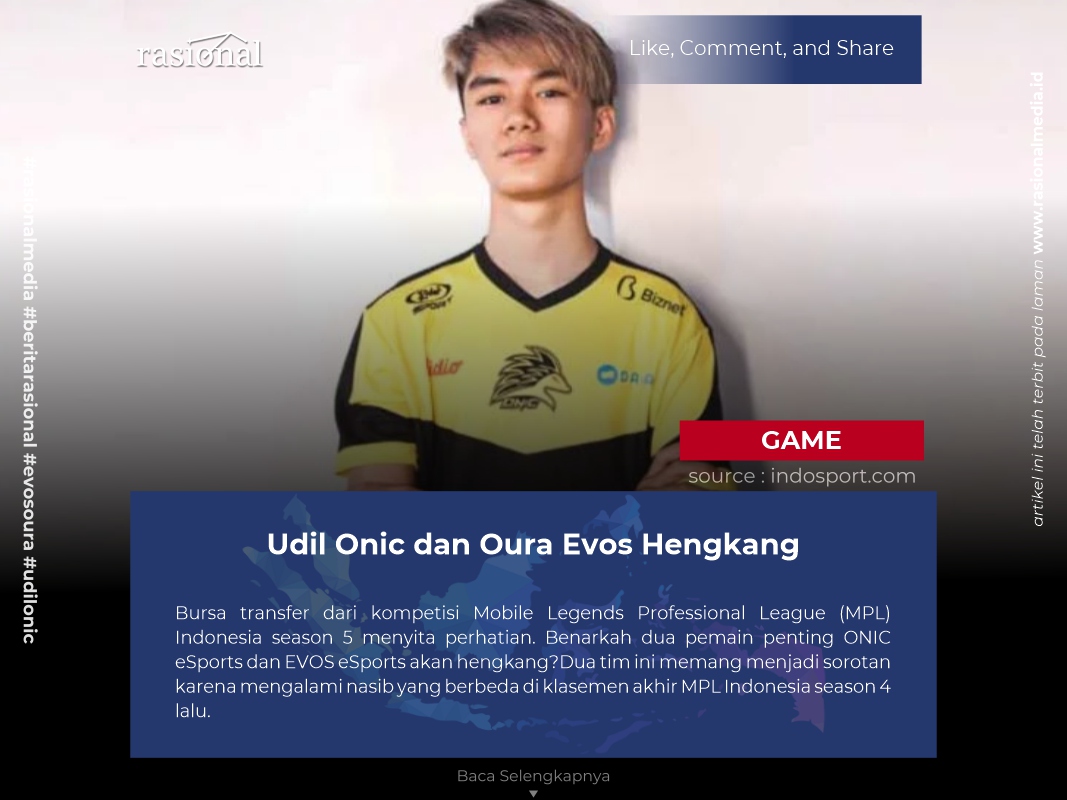








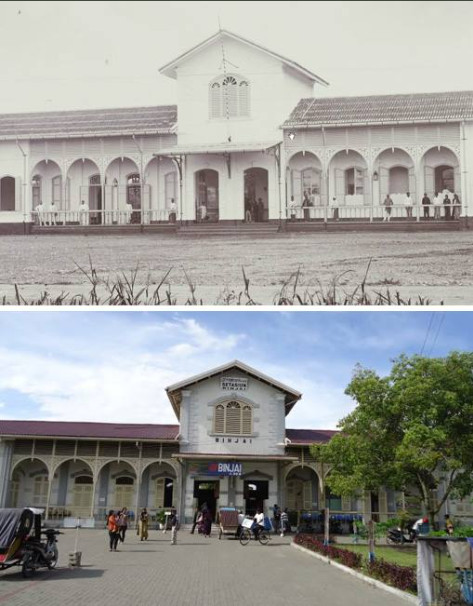



Ada 0 komentar untuk artikel ini